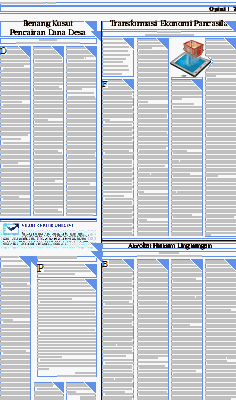
Akrobat Hukum Lingkungan
Opini
KOMPAS edisi 24 Mei 2018
Halaman: 07
Penulis: Agung Wardana
Akrobat Hukum Lingkungan
Akrobat Hukum Lingkungan
Dosen di Departemen Hukum Lingkungan, Fakultas Hukum, UGM
Belakangan ini penegakan hukum lingkungan berangsur memperlihatkan wajah optimisme. Data Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebutkan, dalam kurun 2015-2017, KLHK mengakumulasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Rp 16,6 triliun, yang bersumber dari penggantian kerugian dan pemulihan lingkungan berdasarkan putusan pengadilan. Ini belum termasuk keberhasilan KLHK dalam penggunaan prosedur pidananya.
Namun, optimisme ini tercoreng setelah muncul putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No 16/Pdt-G/2017/PN.Mbo. Perkara ini melibatkan penggugat PT Kalista Alam (KA), perusahaan yang telah diputus oleh Mahkamah Agung untuk membayar kerugian dan pemulihan akibat pembakaran lahan, melawan KLHK sebagai tergugat. Putusan PN Meulaboh tersebut jadi sorotan publik karena terdapat beberapa kejanggalan. Dalam pandangan penulis, setidaknya ada dua kejanggalan, yakni penafsiran atas ne bis in idem (doktrin hukum yang mengajarkan bahwa perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya) dan dasar pengajuan gugatan.
Tafsir atas ”ne bis in idem”
Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap memang dimungkinkan untuk digugat kembali asalkan tidak termasuk dalam kategori ne nebis in idem. Permasalahannya, penafsiran atas makna ne bis in idem jadi problematik dengan adanya ketidaksinkronan yurisprudensi, yakni antara Yurisprudensi No 102K/Sip/1972 dan Yurisprudensi No 1226/K/Pdt/2001.
Yurisprudensi Nomor 102K/ Sip/1972 menyatakan bahwa ”apabila dalam perkara baru ternyata para pihak berbeda dengan pihak-pihak dalam perkara yang sudah diputus lebih dulu, maka tidak ada ’ne bis in idem’.” Sebaliknya, Yurisprudensi Nomor 1226 K/Pdt/2001 menyatakan ”[m]eski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan nebis in idem.” Yurisprudensi mana yang digunakan oleh hakim dalam mengonstruksi putusannya akan ditentukan oleh ”kepentingan” pihak mana yang ”dilayani” oleh hakim tersebut.
Dalam kasus gugatan PT KA, majelis hakim PN Meulaboh memilih menggunakan Yurisprudensi No 120K/Sip/1972. Argumentasi yang dibangun adalah bahwa ada perubahan kedudukan subyek dan ada subyek-subyek hukum baru yang masuk menjadi turut tergugat. Jika dicermati pada pokok perkaranya, para turut tergugat ini memiliki posisi hukum yang justru menguatkan klaim dari pihak penggugat. Yurisprudensi No 1226K/ Pdt/2001 sama sekali tidak dipertimbangkan. Sejatinya, jika terdapat konflik yurisprudensi, semestinya yurisprudensi terbaru yang digunakan karena ia lebih mencerminkan perkembangan hukum dan konteks sosial terkini yang membentuknya.
Kekeliruan obyek sengketa atau kekeliruan panitera
Dalam gugatan yang diajukan, PT KA mendalilkan adanya kekeliruan obyek sengketa (error in objecto) dalam putusan-putusan sebelumnya. Kekeliruan ini, menurut mereka, berangkat dari ketidakakuratan dalam penulisan koordinat batas-batas konsesi perusahaan yang mestinya 96 derajat ditulis menjadi 98 derajat.
Bagi mereka, hal ini berimplikasi pada luasnya konsesi milik PT KA yang membentang hingga Sumatera Utara. Di sini, penulis mengajukan pertanyaan apakah penulisan koordinat 98 derajat dalam putusan sebelumnya merupakan error in objecto sebagaimana didalilkan penggugat atau merupakan clerical error (kekeliruan kepaniteraan).
Dua jenis kekeliruan ini memiliki implikasi hukum yang berbeda. Putusan yang diambil berdasarkan error in objecto akan berakibat pada judicial error (kekeliruan dalam penerapan hukum), tetapi clerical error tidak. Dalam sistem Common Law, tidak seperti dalam kasus judicial error yang harus menggunakan prosedur upaya hukum, clerical error dapat diperbaiki melalui rulingnunc pro tunc (’now for then’), yakni perbaikan atas clerical error dari putusan sebelumnya. Hal ini karena clerical error tidak memiliki implikasi substansial atas pokok perkara.
Dalam konteks putusan atas gugatan PT KA, nature dari koordinat 98 derajat dapat dikaji dengan dua hal. Pertama, sifat dari kekeliruan penulisan koordinat 98 derajat dapat dikaji dengan melakukan penafsiran sistematis. Mengingat PT KA diperkarakan tidak saja secara perdata, tetapi juga secara pidana, penafsiran sistematis dapat dilakukan dengan mengkaji konsistensi penggunaan koordinat 98 derajat di kedua putusan tersebut. Konsistensi penulisan ini penting untuk menilai apakah koordinat 98 derajat dipakai pula dalam perkara pidananya.
Faktanya, dalam putusan perkara pidananya seluruh koordinat konsisten menggunakan angka 96 derajat sebagai lokasi di mana tindak pidana pembakaran hutan dan lahan terjadi. Satu kalimat pun tidak ada menyebutkan koordinat 98 derajat. Artinya, penggunaan 98 derajat hanya ada dalam putusan perdata sehingga hal ini besar kemungkinan merupakan kesalahan ketik (clerical error) semata.
Kedua, pertanyaannya apakah areal berkoordinat 98 derajat merupakan obyek perkara atau hanya informasi pelengkap semata. Dalam gugatan KLHK terhadap PT KA, obyek perkaranya adalah lokasi kebakaran yang berada di tengah konsesi PT KA, utamanya Blok A4 yang memiliki koordinat 96 derajat. Jikalau pun terdapat kekeliruan dalam penulisan koordinat batas-batas konsesi milik PT KA menjadi 98 derajat, hal ini tidak menghilangkan fakta bahwa telah terjadi kebakaran di Blok A4 yang berkoordinat 96 derajat (masih dalam konsesi perusahaan).
Berbeda dengan kasus sengketa tanah yang batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas karena obyek sengketanya tanah tersebut secara menyeluruh, dalam kasus PT KA, yang dijadikan obyek perkara bukan keseluruhan konsesinya, tetapi Blok A4 yang berada dalam konsesi PT KA yang mengalami kebakaran. Dengan demikian, penulisan berkoordinat 98 derajat tidak untuk merujuk pada obyek sengketa, tetapi merupakan informasi tambahan terkait batas-batas konsesi PT KA. Konsekuensinya, kesalahan penulisan koordinat 98 derajat tidak dapat dikatakan sebagai error in objecto karena ia bukan obyek sengketa.
Berdasarkan uraian di atas, telihat jelas bahwa ada yang salah dengan Putusan PN Meulaboh No 16/Pdt-G/2017/PN.Mbo. Kesalahan ini hendaknya jadi pintu masuk untuk refleksi bagi MA jika memang ingin mendorong judicial activism dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jika tidak, akrobat hukum lingkungan seperti ini akan diduplikasi oleh pengadilan lain, mengingat kasus lingkungan memiliki dimensi kepentingan ekonomi dan politik yang kuat.
- Penggunaan artikel wajib mencantumkan kredit atas nama penulis dengan format: ‘Kompas/Penulis Artikel’.
- Penggunaan artikel wajib mencantumkan sumber edisi dengan format: ‘Kompas, tanggal-bulan-tahun’.
- Artikel yang digunakan oleh pelanggan untuk kepentingan komersial harus mendapatkan persetujuan dari Kompas.
- Artikel tidak boleh digunakan sebagai sarana/materi kegiatan atau tindakan yang melanggar norma hukum, sosial, SARA, dan mengandung unsur pelecehan/ pornografi/ pornoaksi/ diskriminasi.
- Pelanggan tidak boleh mengubah, memperbanyak, mengalihwujudkan, memindahtangankan, memperjualbelikan artikel tanpa persetujuan dari Kompas.
Suggestion




